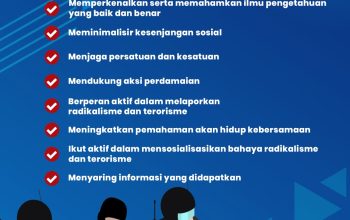Portal.id, Kendari – Seorang ibu menyambut saya disebuah kios, Rabu siang, 8 Januari 2024 lalu. Dialah Zakiatus Sidiqah (34), seorang ibu rumah tangga anggota Jamaah Ahmadiyah di Kota Kendari.
Kios yang menjadi titik temu tersebut adalah milik ibunya, Nurhayati (50) juga anggota Jamaah Ahmadiyah, yang sama-sama datang ke kota ini 21 tahun silam tepatnya di tahun 2003.
Zakiyah dan Ibunya adalah penyintas penyerangan Jamaah Ahmadiyah di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, tahun 2002 silam. Setahun kemudian, Iabersama Ibu, ayah serta kakak dan adiknya hijrah ke Kota Kendari, Sultra.
Laporan Komnas HAM menyebut, penyerangan Jamaah Ahmadiyah di tahun 2002 itu sebagai tragedi kemanusiaanterparah yang dialami pengikut Mirza Gulam Ahmad di Indonesia.
Rabu siang itu, Zakia mengajak untuk ngobrol di rumahnya. Sekitar 50 meter dari kios milik ibunya. Kedua tempat ini dipisahkan jalan setapak, dengan kolam ikan ukuran kecil disekelilingnya.
Zakia tinggal di sebuah rumah petak berbahan kayu yang dibangun memanjang ke samping, di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, tak jauh dari Terminal Baruga.
Rumah berukuran sedang memiliki empat kamar tidur, satu dapur dan satu ruang tengah memanjang menyatu ruang tamu. Bangunan ini beratap seng yang sudah kecoklatan, menandakan usianya yang cukup lama.
Pohon buah yang telah membesar, seperti mangga, rambutan dan lainnya merindangi depan rumah. Dahan dan daunnya melebar meneduhi bangunan tempat jemuran baju, dan halaman seluas lapangan bulu tangkis.
Di rumah yang dicat hijau tipis, dan berlantai semen ini, Zakia dan suami serta seorang anaknya tinggal. Terkadang juga ibunya, saat warung sedang tak ada pembeli, atau ditutup karena libur menjual.
Perempuan berpostur sedang ini membuka pembicaraan dengan ramah, sembari menghidangkan sepiring kudapan dan teh, lalu memulai kisahnya dengan ucapan syukur bisa selamat dari tragedi yang memilukan itu.
Meski sudah 23 tahun berlalu, Ia mengaku ingat seluruh rentetan kejadiannya waktu demi waktu. Ingatan ini bahkan sempat mengganggunya diawal tinggal di Kota Kendari, dan membuatnya phobia dengan keramaian.
Namun perempuan kelahiran Bogor, 20 September 1990 ini mengaku tragedi yang dialaminya tetap jadi pengalaman terbaik, karena peristiwa ini justru menjadi jalan hijrah dari Lombok ke Kota Kendari yang masyarakatnya amat bertoleransi.
Sejak kepindahan dulu, tidak ada yang mempermasalahkan statusnya sebagai anggota Jamaah Ahmadiyah. Ia pun bisamenyelesaikan sekolah di SMP Angkasa, dan lanjut ke SMK 3 Kendari hingga lulus.
“Disini kita mau ibadah, alhamdulilah, bisa tenang. Jualan di pasar tidak ada yang ganggu. Ada acara warga kita juga diundang. Itu kesyukuran kita. Mereka tau siapa kita. Tapi tidak pernah dipermasalahkan,” ungkap Zakia.
Hal itu berbeda semasa dirinya dan keluarga tinggal di Lombok. Sejak kecil dirinya, kerap dipersekusi dimanapun berada, bahkan saat berada di sekolah, dan berpuncak pada tragedi Pancor.
“Waktu sekolah SD, setiap kita belajar agama Islam itu kita disuruh keluar kelas, dikumpulkan sama teman yang Kristen, dan Hindu. Waktu itu saya tidak tahu apa-apa. Pulang sekolah cuma ngadu ke Ibu, dan disuruh sabar saja,” kenang Zakia.
Malam Jahanam di Desa Pancor
Lekat dalam ingatan Zakia, malam itu, Rabu 11 September 2002, saat ratusan orang menyerbu tempat tinggalnya di Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB.
Malam belum larut, baru sekitar pukul 21.00 WITA, saat keheningan suasana sekitar rumah Zakia yang berada di tengah sawah berubah jadi keramaian disertai dentuman batu yang beradu dengan atap.
Caci maki dan sumpah serapah diteriakan para penyerang, sembari melemparkan batu, kayu, botol dan benda lainnya ke arah jendela, pintu, atap dan dinding dari sisi depan, samping serta belakang.
Serangan ini mengagetkan seisi rumah, Zakia yang saat itu masih berusia 11 tahun, bersama kakak, adik serta ibu dan ayahnya masih berkumpul di ruang keluarga usai santap malam, lalu bergegas berlindung ke salah satu kamar.
Listrik dipadamkan para penyerang, dan di tengah suasana gelap gulita waktu itu, ramai teriakan ‘bunuh’ serta ‘bakar’ dari orang-orang yang menyerbu rumahnya. Zakia sekeluarga tiarap berdesakan di bawah tempat tidur.
Saat itu Ayahnya tidak berlindung. Ia menjaga pintu dengan badannya. Tegak berdiri, meski kaki dan kepala tergores pecahan kaca jendela, juga batu dan botol yang menembus atap, menjebol plafon, lalu mendarat di peci juga jari kaki.
Zakia bercerita, saat itu Ia menangis sepanjang malam, air mata keluar, tapi tak ada suara, karena ibu menyumpal mulut dengan baju. Begitu juga dengan kakak, dan mulut adik yang dibekap ibu.
Rasa takut memuncak saat orang-orang masuk ke dalam rumah, dan mulai menjarah barang berharga serta memecahkan banyak barang. Zakia ingat, saat itu Ia dan kakak serta adiknyadirangkul ibu.
“Waktu itu saya pikir, sepertinya kita bakal dibunuh. Saya takut sampai badan gemetar. Dingin tapi berkeringat. Saya lihat Ibu terus berdoa. Saya nangis terus tapi tidak ada suara,” tutur Zakia.
Ditengah ketakutan yang amat sangat, Zakia samar-samar mendengar ucapan lirih ayahnya agar semua ‘siap-siap’. Ini karena para penyerang sedang menyisir seluruh ruang, artinya tak lama lagi mereka akan ketahuan.
Mendengar ucapan itu, Ibu terus merapal doa, komat kamit gerak bibir tanpa suara, Zakia semakin gemetar ketakutan. Iapasrah dan merasa inilah akhirnya, setelah beberapa jam berjibaku dengan rasa takut.
Zakia mengingat jelas, orang-orang menyebut ‘ada bau manusia’ saat mereka berbicara didepan kamar yang ditempatinya. Beberapa diantaranya ada yang mencari korek dan minyak tanah.
Namun tak disangka, pertolongan Tuhan benar-benar datang. Bersamaan pintu kamar satu persatu dijebol pintunya. Ramaisuara ayam dari kandang di belakang rumah, mengalihkan perhatian.
Setengah jam kemudian, suara tembakan polisi menggema di seluruh penjuru sisi di luar rumah. Polisi mengambil alih keadaan, dan membuat para penyerang mundur meninggalkan rumah yang sudah porak-poranda.
“Pas rame kandang ayam dijarah. Mereka pada rebutan sambil teriak ‘bagi ayam’ ‘bagi ayam’ jadi sebagian orang keluar rumah. Kamar kita tidak jadi digedor. Polisi tidak lama datang,” tutur Zakia.
Malam itu, dibawah perlindungan tembakan polisi, Zakia sekeluarga dievakuasi ke Markas Polres Lombok Timur. Diliputirasa takut, Zakia dan lainnya keluar lewat jendela, meniti langkah diantara pecahan kaca.
Ia tiba di Mapolres dengan baju satu-satunya sebagai harta di badan. Rasa takut yang belum hilang membuatnya terjaga semalaman. Keesokan harinya, Zakia baru menyadari pecahan kaca telahmelukai seluruh telapak kakinya.
Saat di kantor polisi ini, Zakia juga bertemu banyak anggota Jamaah Ahmadiyah dari luar Pancor. Penyerangan ini rupanya tidak hanya terjadi di desanya, tapi seluruh wilayah se-LombokTimur.
Meski berada di bawah lindungan polisi, neraka kehidupan rasanya belum usai bagi Zakia dan warga Jamaah Ahmadiyah lainnya. Pasalnya, para penyerang ikut mengepung Polres, danmengancam membakarnya.
Ditempat ini, kehidupan dirasakan Zakia serba sulit. Tidur melantai berdesakan dengan ribuan warga. Makanan tidak tersedia. Ia selalu merasakan kelaparan, karena kerap tidak ada makanan sama sekali.
Di luar pagar Polres, para penyerang masih terus berdemonstrasi menyerukan kebencian dan pengusiran pengikut Ahmadiyah, bahkan lembaga sosial yang hendak membantu dicegat.
“Jadi kita makan indomie dengan air keran. Tidak ada yang berani bantu. Waktu itu ada warung makan dibakar. Mereka membantu kita makanan. Padahal pemilik warung bukan jamaah (Ahmadiyah). Cuma kasihan ke kita saja,” terang Zakia.
Kehidupan dalam suasana ini dijalani Zakia dan warga lainnya di Mapolres selama sebulan lebih. Selama itu, Ia merasa waktu berjalan tanpa kejelasan seperti apa kedepannya dan akan bagaimana.
Dalam suasana itu, satu-satunya kesedihan Zakia adalah tidak bisa bersekolah. Tragedi ini sendiri terjadi tepat seminggu setelah dirinya resmi diterima di salah satu SMP unggulan diLombok Timur.
Tragedi ini benar-benar memupus harapan kembali bersekolah di SMP tersebut. Terlebih setelah kakaknya bercerita, para penyerang yang merusak rumahnya adalah teman, keluarga dan kenalan dari desa tetangga.
“Dua hari setelah penyerangan itu, kakak kembali rumah, dikawal polisi. Niatnya mau ambil baju ganti. Pas datang banyak orang sedang hancurkan rumah. Disitu dia liat pelakunya ternyata teman-temannya dari desa tetangga,” tutur Zakia.
Harapan untuk sekolah bagi Zakia datang beberapa bulan kemudian, tak lama setelah dirinya dan warga Jamaah Ahmadiyah diungsikan ke Asrama Transito di Kelurahan Majeluk, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB.
Menjelang akhir tahun 2002, Zakia dan korban tragedi Pancor yang berusia sekolah lainnya dinaikan ke Bus, yang kemudianmelaju membawa mereka ke Tasikmalaya, Jawa Barat.
Pagi itu sebelum keberangkatan, itulah terakhir kali Zakia melihat kedua orang tuanya. Sekaligus sebagai pengalaman pertama hidup tanpa keduanya, berbulan-bulan lamanya tanpa komunikasi sama sekali.
“Di Tasik, kita tinggal sama orang tua asuh, sekolah di SMP umum, tapi sebagian siswanya anak-anak Ahmadi, jadi tidak ada masalah. Akhir tahun 2003, ayah datang jemput, waktu mau berangkat ke Kendari,” terang Zakia.
Tempat Baru, Harapan Baru
Zakia dan Nurhayati, ibunya, merupakan satu dari puluhan keluarga asal Lombok, yang juga menjadi korban kekerasan dan penyerangan Jamaah Ahmadiyah, dan kini memilih tinggal di Sultra.
Meski berbeda waktu kedatangan, juga berbeda latar belakang tragedi yang dialami, namun seluruh Jamaah Ahmadiyah yangdatang ke Sultra punya keinginan serupa, bisa beribadah dengan tenang.
Kapal yang membawa Zakia dan keluarga tiba di Pelabuhan Nusantara Kendari sekitar November 2003. Dilanjutkan dengan naik angkot, dan berakhir di Kecamatan Baruga, Kota Kendari.
Menyusuri jalan setapak, di sebuah pemukiman di tengah rawa, disitulah Zakia dan keluarga tinggal. Disebuah rumah panggung kecil, pinjaman anggota Jamaah Ahmadiyah yang tinggal diwilayah ini.
“Waktu kita tiba di rumah, kita kaget. Wah kok begini. Rumah panggung, diatas rawa. Banyak nyamuk. Ibu sempat merasa tidak sreg. Tapi dia tetap menerima, yang penting bisa ibadah tenang, dan anak-anaknya bisa sekolah,” ungkap Zakia.
Zakia menyebut, atas tragedi Pancor, ibunya diakui yang paling terpukul. Sebab, Ia sudah berniat membangun masa depan di Lombok. Setiap hari bekerja di Pasar Besar Pancor, berjualan, dan hasilnya ditabung.
Dari tabungan itu dibelikan tanah, dan dibangunkan rumah permanen sedikit demi sedikit hingga tahunan, yang tepat baru selesai seluruhnya di tahun 2002. Sayangnya, sore hari rumah itu baru selesai di cat, malamnya dihancurkan.
Meski harus berjuang dari nol, Zakia menuturkan, ayahnya, Rehanuddin Ahmad tetap teguh. Terlebih, Ia begitu takjub dengan kebaikan orang – orang disekitar tempat tinggalnya, yang begitu menjunjung toleransi.
Ia tidak pernah menyembunyikan identitasnya sebagai pengikut Ahmadiyah, tujuannya untuk mengukur resistensi warga sekitar, kalau tidak ada kecocokan, rencananya bakal segera pindah.
Ternyata selama tahun-tahun awal mendiami wilayah ini. Tak ada penolakan, baik dalam aktifitas dakwah, hubungan sosial dengan warga setempat, atau soal ekonomi dan pekerjaan, meski mereka pendatang.
Agar dapur tetap ngebul, Ayah bekerja sebagai tukang sol sepatu, servis payung, menjual ikan, atau pekerjaan serabutanlainnya. Semua dilakukan tanpa melupakan tanggung jawabnya sebagai mubaligh.
Uniknya, aktivitas dakwah dilakukan tidak hanya bagi warga Jamaah Ahmadiah, tapi juga di luar jamaah, diantaranya seperti mengajar ngaji, membawakan ceramah, atau membacakan doadi acara warga.
Zakia bercerita, keleluasaan beribadah jadi faktor utama dirinya dan keluarga betah tinggal di Kota Kendari, faktor lainnya ialah kebaikan orang-orang yang menerima perbedaan berkeyakinan.
“Jadi waktu awal itu kita rasa, ya lumayan berat juga. Tapi orang-orang sini baik, ayah kerja serabutan. Tapi tidak pernah nganggur. Selalu ada yang bisa dikerjakan, orang-orang selalu panggil untuk kasih kerjaan,” ujar Zakia.
Ayah Zakia sendiri telah wafat pada tahun 2019 lalu, tepat saat Raya Idul Fitri. Ia roboh saat membawakan khutbah ied di hadapan ratusan Jamaah Ahmadiyah yang memadati Rumah Misi, yang juga pusat dakwah JAI di Kota Kendari.
Sebelum wafat, kata Zakia, ayahnya berpesan untuk banyak mengabdikan dirinya bagi masyarakat di Sultra. Ia merasa ayahnya amat berterimakasih atas kebaikan banyak orang yang membantunya di masa sulit.
Zakia telah menikah di tahun 2008, seorang seorang pemuda dari kalangan Jamaah Ahmadiyah, asal dari Lombok jadi suaminya. Namun Ia baru datang ke Kota Kendari beberapa tahun setelah kedatangannya.
Saat tengah membangun keluarga kecilnya, secara tersirat Zakia mengaku diminta ayahnya untuk tetap tinggal di Sultra, dan menata hidupnya sepeninggalnya kelak, dan pesan itu tetap dipegangnya hingga kini.
“Ayah pernah kasih nasihat. Kita sudah maafkan orang-orang di Lombok yang menghancurkan rumah kita. Tapi kalau untuktinggal demi masa depan. Jangan pernah tinggalkan Sultra,” terang Zakia.
Sepeninggal ayahnya, Zakia kini menjalani hari-harinya dengan berjualan aneka jajanan di gerai UMKM miliknya tak jauh dari Pasar Baruga. Selain itu, Ia menyibukan diri dengan beribadah.
Seperti warga Jamaah Ahmadiyah asal Lombok yang datang di Sultra lainnya. Ibadah menjadi aktifitas utama, sebagai tujuan awal meninggalkan tanah kelahirannya di ‘Pulau Seribu Masjid’.
Ia juga tidak pernah melewatkan kesempatan mengikuti muawanah sebagai agenda syiar dan silaturahmi bagi kalangan perempuan dan ibu-ibu Jamaah Ahmadiyah, yang dilaksanakan sekali sebulan.
Zakia menyebut, cerita indahnya toleransi dan kebebasan beragama di Sultra sendiri, masih terus menjadi harap dan mimpi bagi warga Jamaah Ahmadiyah di Lombok hingga saat ini.
Meski demikian, masih banyak pula rekan sejawatnya yang memilih untuk bertahan. Umumnya karena merasa berat meninggalkan keluarga, dan harta benda, juga karena trauma.
“Kan kalau kita, tanah, kebun itu semua kita tinggal. Kalo yang lain mungkin berat. Berjuang dari nol itu juga kan juga tidak gampang. Kalau kita cukup bismillah, berangkat. dan alhamdulillah di Sultra semuanya lebih baik, khususnya dalam hal ibadah,” pungkasnya.
Memijak Bumi, Menjunjung Langit
Rentang waktu 2007-2020, SETARA Institute mencatat ada 2.713 peristiwa pelanggaran Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan(KBB) di Indonesia. Dari jumlah itu, Jamaah Ahmadiyah menjadi penganut yang paling banyak mengalami peristiwa pelanggaran KBB, yakni 570 peristiwa.
Angka ini menandakan begitu tinggi resistensi yang dialami Jamaah Ahmadiyah secara umum di Indonesia. Meski demikian, kondisi tersebut tampaknya berbanding terbalik dengan yang ada di Sultra.
JAI Sultra mencatat, satu-satunya peristiwa pelanggaran KKB terjadi pada tahun 2006 silam, di Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konsel. Selain peristiwa itu, hubungan antar umat beragama berjalan baik.
“Tahun 1960-an juga pernah terjadi tindakan represif, itu dialami pengurus awal JAI di Sultra, tapi itu diera orde baru, segala sesuatu memang serba represif saat itu,” ungkap Mubaligh Daerah (Mubda) JAI Wilayah Sultra Aang Kunaefi.
Menurutnya, penerimaan yang baik bagi pengikut Jamaah Ahmadiyah saat ini, merupakan buah kerja keras mubaligh JAI dalam mengemban misi dakwah di masa awal Ahmadiyah di Sultra era tahun 60-an tersebut.
JAI sendiri berkomitmen dijalan dakwah yang mengajarkan perdamaian, cinta, keadilan, dan kesucian hidup, sebagai bagian pokok ajaran Ahmadiyah yang dipelopori Mirza Ghulam Ahmaddi India pada 23 Maret 1889.
Visi gerakan dakwah yang dilakukan mubaligh JAI Wilayah Sultra ini membuat pengikut Jamaah Ahmadiyah yang disebut Ahmadi bisa diterima hingga kini dan hidup berdampingan dengan umat beragama yang berbeda-beda.
Tak hanya, itu sejak dua dekade silam, ajaran Ahmadiyah juga sudah mulai diterima sebagian masyarakat lokal Sultra, meskipun dalam jumlah yang sedikit, dibanding jumlah jamaah dari para pendatang.
Berdasarkan data JAI Sultra, jumlah pengikut Ahmadiyah sekitar 1000 orang lebih dengan jumlah terbesar berdomisili di Konawe Selatan, dan umumnya merupakan pendatang asal Jawa, Jawa Barat, juga sekitar 100-an persen warga lokal.
“Jumlah jamaah terbesar masih para pendatang. Tapi menambah jumlah pengikut bukan target kita. Dakwah kita fokus bagaimana jamaah meningkatkan kualitas keimanan dan beribadah dengan benar. Tapi kita terbuka jika ada yang ingin berdiskusi,” ungkap Aang.
Aang sendiri adalah mubaligh yang dikirim JAI Pusat untuk berdakwah, dan membina keumatan serta mengurus dan menata struktur kelembagaan JAI cabang di seluruh kabupaten dan kotase Provinsi Sultra.
Sebelum bertugas di Sultra, dirinya pernah bertugas di Manado, Gorontalo, Kuningan dan Tasikmalaya. Sebelum akhirnya ditugaskan di Kota Kendari sebagai mubaligh daerah sejak limatahun lalu.
Dari pengalamannya disejumlah daerah itu, Ia menilai Sultra ibarat ‘oase ditengah gurun’ dalam hal toleransi dan hubungan antar umat beragama, hubungan antar ormas keagamaan dan pemerintah.
“Toleransi masyarakat Sultra amat baik. Makanya, jamaah korban kekerasan berharap bisa tinggal dsini, agar bisa beribadah dengan tenang. Tapi kami selalu tekankan untuk berprinsip ‘dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung’,” ungkap Aang.
Senada dengan itu, Amir Daerah JAI Wilayah Sultra, Ahmad Sewangi menyebut, sejak beberapa tahun silam, puluhan kepala keluarga warga Jamaah Ahmadiyah asal Lombok penyintas kasus kekerasan memilih tinggal di Sultra.
Meski demikian, kedatangan para korban kekerasan dan pelanggaran KKB ini tidak sekaligus, terjadi secara bengangsur-angsur, atas koordinasi dengan JAI Pusat yang berkedudukan diParung, Bogor, Jawa Barat.
“Tidak serta merta datang. Kita pastikan tempat kalau dia petani, kita titip di daerah pertanian, kalau pedagang kita berikan tempat yang sesuai. Agar bisa membangun ekonominya sendiri,” terang Ustad Ahmad.
Diungkapkannya, hubungan serta toleransi antar umat beragama yang begitu baik di daerah ini, membuat JAI Sultra berperan penting dalam menghadirkan resolusi konflik, khususnya bagikorban kekerasan.
Tidak hanya itu, Sultra juga menghadirkan bagi pengikut Jamaah Ahmadiyah diseluruh Indonesia, sebagai tempat untuk menjalankan ibadah dengan tenang tanpa gangguan, ancaman dan rasa was-was.
“Mereka orang-orang yang kehilangan harta benda.Keinginannya sederhana, hanya ingin beribadah dengan tenang. Harapan itu nanti baru tumbuh setelah tiba di Sultra,” ujar Ahmad.
Hal ini jua yang diungkapkan Ustad Muhyi, seorang mubaligh muda JAI, yang sejak tahun 2022 lalu bertugas di Kabupaten Konawe, Sultra, sebagai penugasan perdana usai menuntaskan pendidikan.
Muhyi adalah penyintas kekerasan Jamaah Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, tahun 2006, yang berujung perusakan, pembakaran dan pengusiran warga.
Dalam peristiwa tersebut sedikitnya 132 orang warga Ahmadiyah terpaksa mengungsi ke Asrama Transito, di Majeluk, Kota Mataram, NTB, dan masih bertahan hingga saat ini, setelah 19 tahun pasca kejadian.
Asrama Transito sendiri awalnya adalah tempat penampungan transmigran asal Jawa. Pasca rentetan konflik, bangunan seluas setengah hektar ini difungsikan sebagai pengungsian bagi Jamaah Ahmadiyah.
Muhyi bercerita, ditempat yang sempit dan penuh sesak inilah, bapak, ibu, dua orang adik, dan seorang kakaknya tinggal berdesakan dengan ratusan jamaah korban kekerasan dari berbagai wilayah.
Kondisi bangunan tidak layak, jauh dari rasa kemanusiaan serta aksi perundungan yang tidak menyurut dari warga sekitar hingga saat ini, menjadi alasan dirinya ingin memboyong keluarga meninggalkan tanah kelahirannya itu.
“Sebenarnya kami ada keinginan untuk keluar dari transito, tapi kami bertahan disana untuk melihat bagaimana pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus di pengungsian,” ujar Muhyi.
Kelompok Intoleran Jadi Tantangan
Antropolog Universitas Halu Oleo (UHO) Danial menilai, sisi penting dari eksistensi gerakan dakwah Jemaat Ahmadiyah diSultra, berada pada bauran secara kultural dengan masyarakat lokal.
Hal itu didukung budaya hubungan masyarakat etnis asli Sultra yang secara kultural merupakan kelompok masyarakat terbuka dan berjiwa sosial tinggi, baik di tinggal daratan maupun kepulauan.
Budaya inilah juga yang menjadi faktor penting kesuksesan program transmigrasi era Orde Baru sejak tahun 50-an, baik di daratan seperti Konsel, Kolaka, juga di kepulauan seperti Buton,Muna dan pulau lainnya.
Hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat asli Sultra dan pendatang itu esensinya ada pada hubungan kultural. Hal ini bersesuaian dengan misi dakwah Jamaah Ahmadiyah yang menyerap nilai kultural masyarakat lokal.
“Orang Bali, Jawa, Sunda, maupun etnis lain bisa hidup berdampingan dengan masyarakat lokal. Karena misalnya di Buton ada tradisi haroa atau baca-baca doa. Mereka diundang, datang duduk bersama, tidak ada pertentangan,” ujar Dani.
Kondisi bisa menjelaskan, bagaimana eksistensi gerakan dakwah Jamaah Ahmadiyah bisa diterima masyarakat lokal, karena tidak adanya pertentangan dengan nilai tradisi lokal yangada.
“Muslim di Sultra adalah masyarakat Islam religius kultural yang kuat. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Ketika dua hal ini dihargai. Maka, penghargaan yang sama akan diberikan wargalokal bagi para pendatang,” ungkap Dani.
Menurutnya, hal itu berbeda dengan gerakan dakwah yang dianut kelompok Wahabi, yang baru sekitar dua dekade hadir di Sultra. Namun gerakan dakwah kelompok ini cukup resisten dengan masyarakat lokal.
Pengajar di Fakultas Ilmu Budaya UHO ini menilai, kelompok Wahabi inilah yang menjadi tantangan kedepan, bukan hanyabagi pengikut Jamaah Ahmadiyah, tapi juga Syiah dan ajaran lainnya termasuk penghayat kepercayaan.
Karena jejak intolerasi kelompok ini sudah terlihat, salah satunya misalnya ditunjukan pada aksi pembubaran paksaPerayaan Asyura yang dilakukan pengikut Syiah di Kota Kendari pada 2016 lalu.
“Jadi kalo diliat secara kultural, saya kira tidak akan ada masalah, karena Jamaah Ahmadiyah bisa membaur dalam tradisi masyarakat lokal. Tapi kelompok intoleran ini kedepannya yang jadi tantangan,” ungkap Dani.
Reporter: Taufik Qurahman
Editor: Taufik Qurahman